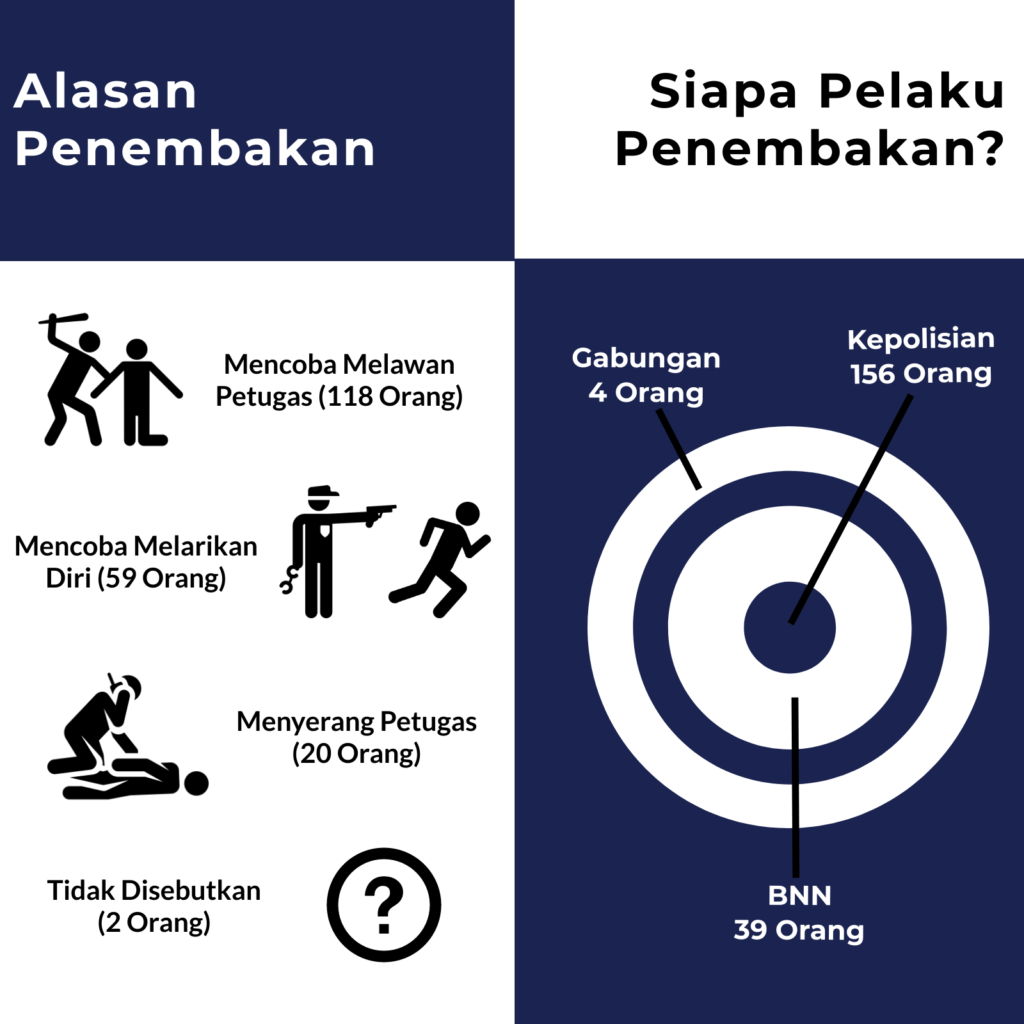Rilis Pers – Menggugat Kebijakan COVID-19 Pemerintah Indonesia
Indonesia secara resmi mengakui merebaknya wabah COVID-19 pada 2 Maret 2020 dengan diumumkannya dua pasien pertama oleh Presiden Joko Widodo. Sejak itu, peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat di Indonesia. Hingga 13 Maret 2020 , pernyataan resmi pemerintah menyebutkan terdapat 35 orang yang positif terinfeksi, 3 orang dinyatakan sembuh dan 2 orang meninggal dunia. Seiring dengan makin luasnya korban, makin besar pula kekhawatiran kami menyangkut cara pemerintah merespons COVID-19:
Pertama, saat pertama kali virus ini muncul di China dan menyebar ke kawasan lain di negara tetangga, pemerintah menganut premis yang sama sekali keliru. Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitnya cenderung meremehkan dan menyiratkan seakan-akan orang Indonesia kebal terhadap serangan virus ini. Prediksi dari Universitas Harvard yang menyebutkan bahwa virus itu sudah sampai di Indonesia, ditolak mentah-mentah, dan bukannya dijadikan landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi virus ini. Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap manakala virus ini benar-benar datang. Sementara para pemimpin negara-negara tetangga jauh-jauh hari sudah mempersiapkan negaranya masing-masing: memperluas kampanye layanan masyarakat, menyiapkan rumah sakit, menetapkan prosedur dan protokol di pelbagai sarana publik, Pemerintah Indonesia terlihat minim inisiatif dan ketinggalan.
Kedua, kegagapan ini nampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah pusat, maupun daerah. Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, miskomunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya nampak dalam bagaimana kasus pertama diumumkan, termasuk pelanggaran hak privasi pasien. Nampak jelas bahwa pemerintah cenderung mendahulukan citra ketimbang kemaslahatan pasien dan keselamatan publik yang lebih luas.
Ketiga, premis yang keliru dalam merespon wabah COVID-19 juga nampak sangat jelas dalam kebijakan pemerintah di awal virus ini masuk. Ketimbang mencurahkan perhatian dan dana untuk mengantisipasi dan menangani virus, pemerintah malah memberikan insentif yang tak masuk akal untuk industri pariwisata termasuk membayar buzzer, bukannya mengucurkan dana untuk fasilitas kesehatan. Sementara negara-negara lain mengetatkan pintu masuk untuk menghindari perluasan virus, Indonesia malah membuka diri lebar-lebar dengan alasan melindungi industri pariwisatanya.
Keempat, kesalahan premis dan kegagapan ini makin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah berulang kali menyerukan ancaman hoaks. Sayangnya kekhawatiran akan penyebaran hoaks, tidak disertai dengan upaya untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang terpercaya dan komprehensif. Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai daampak virus ini terhadap pasien dan lokasi-lokasi penularannya. Kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan praktik di negara lain yang sama-sama sedang menanggulangi COVID-19. Pemerintah Korea Selatan misalnya, secara berkala menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus. Informasi yang terang, disertasi dengan kepekaan untuk mencegah kepanikan dan stigma terbukti sangat bermanfaat untuk membangun kewaspadaan dan mekanisme kehati-hatian publik. Ketertutupan informasi, justru akan memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah. Dalam banyak pengalaman sejarah, informasi yang asimetris justru merupakan penyebab dari parahnya bencana.
Kami menyesalkan dan mengugat cara pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah sama sekali jauh dari pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat yang memerintahkan negara untuk ‘melindungi segenap tumpah darah Indonesia’. Komunikasi publik pemerintah memang bisa mencegah kepanikan, tapi tidak bisa memberikan keamanan dan perlindungan atas ancaman yang nyata. Oleh karena itu kami menuntut:
Pertama, pemerintah harus mengubah dan memperbaiki mekanisme respon atas pandemik ini dengan cara:
1. Menyediakan informasi publik yang benar, lengkap dan berkala menyangkut penyebaran dan risiko penularan.
2. Respons darurat yang cepat, kompeten dan dapat dijangkau masyarakat yang merasa sakit.
3. Menjamin mutu manajemen penelusuran kasus yang teliti dan transparan. Identifikasi klaster-klaster yang positif, lacak orang-orang yang berpotensi tertular atau jadi carrier. Bila perlu lakukan upaya ‘partial isolation’.
4. Pemantauan yang cermat.
5. Kebijakan kesehatan publik yang rasional, dapat dijangkau dan tepat.
6. Uji laboratorium yang luas, tidak boleh dimonopoli Kemenkes, dengan juga memperbanyak testing. Mendukung upaya pemerintah daerah melakukan uji laboratorium untuk pengujian pasien.
7. Manajemen kasus yang baik untuk menghindari stigma terhadap pasien.
8. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang cermat, terpercaya. Manajemen keramaian publik termasuk melarang acara publik.
Respon pemerintah yang cepat, akurat dan bertanggung jawab justru akan berdampak positif karena akan memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kesiapan warga.
Kedua, membenahi manajemen komunikasi publik dengaan membatasi dan bila perlu melarang semua bentuk komunikasi publik dari para pejabat yang tidak memiliki relevansi dan/atau kepakaran di bidang medis, atau kesehatan publik. Termasuk media, sebaiknya juga tidak perlu mencari narasumber/pendapat dari pejabat atau orang-orang yang tidak memiliki keahilian di bidang kesehatan.
Ketiga, pemerintah harus tetap menjaga hak privasi warga. Pengungkapan kasus, informasi tentang penularan bisa dilakukan tanpa harus membuka identitas pasien.
Keempat, mengingat potensi stigma dan diskriminasi yang tinggi terhadap orang yang bisa saja memiliki COVID-19, pemerintah harus memastikan upaya untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi.
Kelima, pemerintah harus turun tangan secara nyata untuk mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik supaya tersedia di masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Jakarta, 13 Maret 2020
AJAR, Amnesty International Indonesia, KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat,
P2D, PKBI, PSHK, YLBHI, YLKI, WALHI
Narahubung:
Ricky Gunawan +681210677657
Anis Hidayah +6281578722874