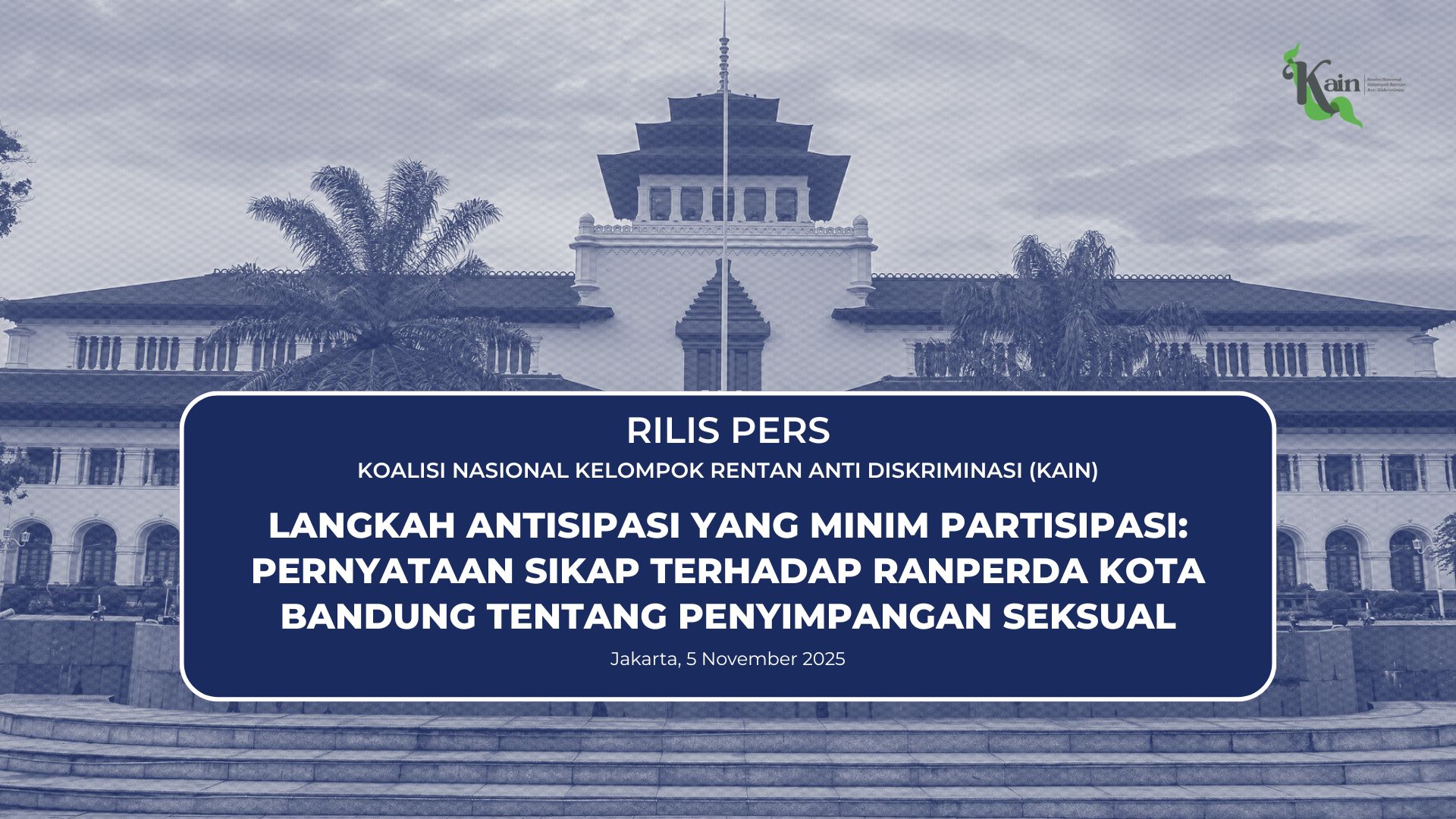Prestasi atau Hipokrisi? Empat Catatan LBHM atas Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mengingatkan bahwa pencapaian pemerintah Indonesia menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB – UN Human Rights Council) harus diikuti dengan komitmen pemerintah yang lebih besar untuk memperjuangkan HAM baik di dalam maupun luar negeri.
Pada tanggal 8 Januari lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Kepemimpinan di Dewan HAM PBB dirotasi setiap tahunnya mewakili grup regional. Tahun ini merupakan giliran Grup Asia Pasifik dan Indonesia mendapatkan nominasi tunggal dari kawasan ini.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memiliki tugas yang berat. Presiden bertanggung jawab memimpin sesi-sesi Dewan HAM, mengajukan kandidat untuk mengisi ahli yang bertugas di prosedur khusus PBB, berkorespondensi dengan kantor perutusan tetap (permanent mission) negara-negara lain, serta melakukan penjangkauan dan diplomasi untuk memperkuat kredibilitas mekanisme Dewan HAM PBB. Dalam pidatonya, pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, juga menyampaikan bahwa Indonesia “akan percaya dan berkomitmen penuh atas prinsip utama universalitas, objektivitas, dan non-selektif dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia.”
Tanggung jawab besar ini sulit untuk dicapai jika sikap Indonesia terhadap permasalahan HAM domestik, regional, dan internasional masih “begini-begini” saja. Untuk itu, LBHM memberikan empat rekomendasi mengenai bagaimana Pemerintah Indonesia bisa menjalankan amanahnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara lebih wahid.
Pertama, pemerintah Indonesia perlu menjadi pemain aktif dalam menyuarakan isu-isu HAM kontemporer di sesi Dewan HAM PBB.
Selama ini, meskipun sudah enam periode menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia masih pasif dalam menunjukkan keberpihakannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dunia di sidang-sidang Dewan HAM PBB. Indonesia hanya menjadi sponsor utama (main sponsor) atas 9 dari 193 resolusi yang dirumuskan dalam sidang Dewan HAM PBB selama tahun 2024-2025. Yang lebih ironis lagi, di antara 9 resolusi ini, catatan kami menunjukkan Indonesia tidak pernah menjadi penanggung jawab (pen holder), yang umumnya bertanggung jawab menuliskan draft awal dan menjadi penanggung jawab utama dari resolusi.
Prestasi ini kalah dari negara-negara lain yang juga termasuk sebagai negara Global South. Misalnya, sepanjang 2024-2025, Brazil menjadi sponsor utama sebanyak 21 kali yang mana 5 di antaranya mereka menjadi pen holder; Ghana 9 kali menjadi sponsor utama yang mana 7 di antara menjadi pen holder.
Absennya Indonesia untuk menjadi pen holder dalam pembuatan resolusi membuat posisi Indonesia di forum internasional ini menjadi ambigu. Tentu baik untuk mendukung banyak resolusi dengan berbagai tema, tetapi dunia internasional perlu juga mengetahui apa ciri khas perjuangan HAM Indonesia. Misalnya, sebagai salah satu negara yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia bisa secara konsisten memperjuangkan hak bebas dari diskriminasi bagi semua, terlepas apapun identitasnya, di forum HAM tertinggi di dunia ini.
Kedua, misi menghapus penjajahan di dunia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 harus mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam mendorong resolusi yang memajukan pemenuhan HAM di suatu negara.
Salah satu pernyataan yang paling bombastis tentang mandat kepresidenan Dewan HAM datang dari Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menangani masalah HAM di Venezuela. Sayangnya, ambisi untuk menjadi pihak yang mampu untuk memecahkan permasalahan HAM dan krisis humaniter dunia tidak tercermin dari posisi Indonesia selama ini di Dewan HAM PBB.
Selain tidak pernah menjadi sponsor utama di resolusi yang spesifik membahas krisis HAM di suatu negara di periode 2024-2025, Indonesia juga cenderung bersikap abstain bahkan menolak resolusi-resolusi seperti ini. Misalnya, Indonesia menolak sebuah resolusi pada Oktober 2025 terkait dengan kondisi krisis humaniter di Sudan akibat konflik bersenjata yang menyebabkan 12 juta orang terusir. Indonesia juga seolah masih bermain ‘aman’ di resolusi-resolusi menyangkut negara-negara yang selama ini menjadi proksi negara sahabat Indonesia, misalnya resolusi yang menyangkut soal Burundi, Belarus, Syria, dan negara-negara lainnya.
Jikapun alasan untuk memilih tidak menyetujui atau abstain dari resolusi-resolusi ini adalah untuk menghargai kedaulatan suatu negara, perwakilan Indonesia seharusnya juga menawarkan resolusi lain yang lebih konstruktif. Misalnya, resolusi yang mendorong adanya tim independen untuk meninjau situasi pemenuhan HAM di sana atau menyarankan asistensi bagi negara tersebut untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya, dan lain-lain. Diplomasi yang bebas aktif menuntut Indonesia untuk secara kreatif menawarkan solusi dan menjembatani antara kedaulatan dan kemanusiaan.
Ketiga, Indonesia perlu menunjukkan dukungan yang bermakna pada prosedur-prosedur khusus yang tercipta dalam forum Dewan HAM PBB.
Salah satu keunggulan Dewan HAM PBB adalah kemampuannya untuk membentuk prosedur khusus (special procedures) untuk mendalami permasalahan HAM tertentu atau permasalahan HAM yang terjadi di suatu kawasan tertentu. Biasanya, prosedur khusus ini hadir dalam bentuk pelapor khusus (special rapporteur), ahli independen (independent expert), kelompok kerja (working group), dan lain-lain. Per November 2025, ada 59 prosedur khusus dengan beragam tipenya. Prosedur khusus memiliki kewenangan untuk melakukan kunjungan ke negara, berkomunikasi dengan negara, membuat standar HAM internasional, memberikan nasihat kepada negara untuk meningkatkan pemenuhan HAM di negara tersebut.
Dukungan bagi prosedur khusus ini bukan hanya dalam bentuk menerima laporan mereka yang disajikan di sidang Dewan HAM PBB, tetapi juga dalam menerima kunjungan mereka untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri. Sayangnya, pemerintah Indonesia seperti alergi atas kunjungan dari para prosedur khusus ini. Dari sekian banyak prosedur khusus yang ada dan menginginkan untuk mengunjungi Indonesia, baru ada sepuluh prosedur khusus yang diizinkan masuk ke Indonesia. Yang terakhir mendapat izin masuk ke Indonesia adalah Pelapor Khusus untuk Myanmar pada 13-21 Juni 2023. Sebanyak 33 prosedur khusus sudah meminta izin masuk ke Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia mengabaikan permintaan mereka atau menolak mereka untuk datang.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia semestinya bisa memberikan dukungan yang lebih besar atas mekanisme-mekanisme khusus ini. Mereka telah dipilih lewat proses yang tidak mudah dan mereka memiliki riwayat pekerjaan atau pendidikan yang memadai untuk memberikan bantuan teknikal bagi Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM di sini. Kursi presidensi Dewan HAM PBB seharusnya menjadi momentum pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih terbuka atas masukan para ahli.
Keempat, tanpa pembenahan permasalahan HAM di dalam negeri, kepresidenan Indonesia di Dewan HAM PBB berpotensi dipandang sebagai hipokrisi antara komitmen internasional dan praktik domestik.
“Foreign policy begins at home.” Agak tidak afdol rasanya jika Indonesia membangun reputasi internasional sebagai pejuang HAM ketika kondisi pemenuhan HAM di dalam negeri porak-poranda.
Pekerjaan rumah Indonesia di isu kebebasan dan hak tidak sedikit. LBHM masih mencatat pelanggaran hak atas hidup, hak atas peradilan yang adil, hak untuk bebas dari diskriminasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak kelompok rentan. Pada tahun 2025, ada 619 orang yang terancam nyawanya karena hukuman mati. Catatan LBHM tentang aksi penyiksaan dan pelanggaran hak atas peradilan yang adil bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum juga masih panjang. Di sisi lain, negara seperti abai atas persekusi yang dialami oleh kelompok rentan, seperti kelompok keberagaman gender dan seksualitas.
Bahkan yang lebih buruk lagi, jangan sampai apa yang disampaikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB kontradiktif dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Ini pernah terjadi. Pada Sesi Dewan HAM PBB ke-59, Indonesia menjadi sponsor utama dari resolusi berjudul “Hak untuk Bebas Berkumpul dan Berasosiasi Secara Damai” yang mendorong negara-negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kebebasan seseorang untuk berkumpul dan berasosiasi secara damai terlepas dari kewarganegaraan, etnisitas, agama, pekerjaan, gender, dan lainnya. Dua bulan sesudah resolusi yang diperjuangkan oleh Utusan Tetap Indonesia di Jenewa ini disepakati secara konsensus, terjadi penangkapan besar-besaran aktivis dan orang-orang yang berunjuk rasa di Demo Agustus 2025; kurang lebih 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan label sembrono ‘pelaku kerusuhan’.
Dengan dipegangnya mandat kepresidenan Dewan HAM PBB, Indonesia perlu lebih banyak menghubungkan pernyataan-pernyataan manis di depan para diplomat dengan kondisi riil yang ada di jalanan, di tempat-tempat penahanan, di institusi-institusi dasar, di layanan publik. Jika tidak dilakukan, selamanya jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dianggap gimmick belaka.
Empat catatan yang LBHM serukan tidak menutup apresiasi kami atas kerja keras Pemerintah Indonesia dalam mendapatkan kursi kepresidenan Dewan HAM PBB. Namun, upaya mendapatkan kursi itu harusnya juga dibarengi dengan kemampuan untuk meningkatkan keaktifan, menjaga kualitas kepemimpinan, dan secara konsisten bersuara lantang menentang pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan internasional, regional, dan domestik.
“Jangan sampai jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini hanya sebagai upaya pencitraan pemerintah untuk mengelak dari kritik publik atas permasalahan-permasalahan serius HAM di dalam negeri,” jelas Albert Wirya, Direktur LBHM. “Pemerintah Indonesia perlu memperlihatkan bahwa jabatan ini betul sebagai prestasi, bukan semata hipokrisi.”
Jakarta, 9 Januari 2026
Narahubung:
Albert Wirya, +62 852-1524-1116, awirya@lbhmasyarakat.org
Referensi:
- Eva Safitri “Pertama Kalinya, Indonesia Resmi Jadi Presidensi Dewan HAM PBB 2026,” detik.com, 8 Januari 2026, diakses di https://news.detik.com/berita/d-8298347/pertama-kalinya-indonesia-resmi-jadi-presidensi-dewan-ham-pbb-2026.
- “Human Rights Council President,” diakses di https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/presidency
- Jayanty Nada Shofa, “Indonesia Officially Becomes UN Human Rights Council President,” jakartaglobe.id, 8 Januari 2026, diakses di https://jakartaglobe.id/news/indonesia-officially-becomes-un-human-rights-council-president
- Haryanti Puspa Sari dan Jessi Carina,”Natalius Pigai Sebut Indonesia Cetak Sejarah Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Akan Tangani Venezuela,” kompas.com, 6 Januari 2026, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2026/01/06/16383791/natalius-pigai-sebut-indonesia-cetak-sejarah-jadi-presiden-dewan-ham-pbb.
- Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 October 2025: 60/3. Responding to the human rights and humanitarian crisis caused by the ongoing armed conflict in the Sudan,” 7 Oktober 2025, A/HRC/RES/60/3
- Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 October 2025: 0/15. Situation of human rights in Burundi,” 7 Oktober 2025, A/HRC/RES/60/15
- Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 3 April 2025 58/19. Situation of human rights in Belarus,” 4 April 2025, 7 Oktober 2025, A/HRC/RES/58/19
- Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 10 October 2024 57/21. Situation of human rights in the Syrian Arab Republic,” 14 Oktober 2024, A/HRC/RES/57/21.
- “About special procedures,” ohchr.org, diakses di https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council
- Data bisa dilihat di https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&lang=en
- Data bisa dilihat di https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&lang=en
- Data per 31 Desember 2025, dilihat di https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Laporan Tahunan 2024 Tersesat Dalam Transisi: Rakyat Berjuang Menavigasi, (Jakarta, 2025), diakses di https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2025/02/Indo-Layout-Laporan-Tahunan-2024-1.pdf
- Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 4 July 2025: 59/4. The rights to freedom of peaceful assembly and of association ,” 8 Juli 2025, A/HRC/RES/59/4.
- Divisi Humas Polri, “959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusuhan Demonstrasi Akhir Agustus 2025,” 24 September 2025, diakses di https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025