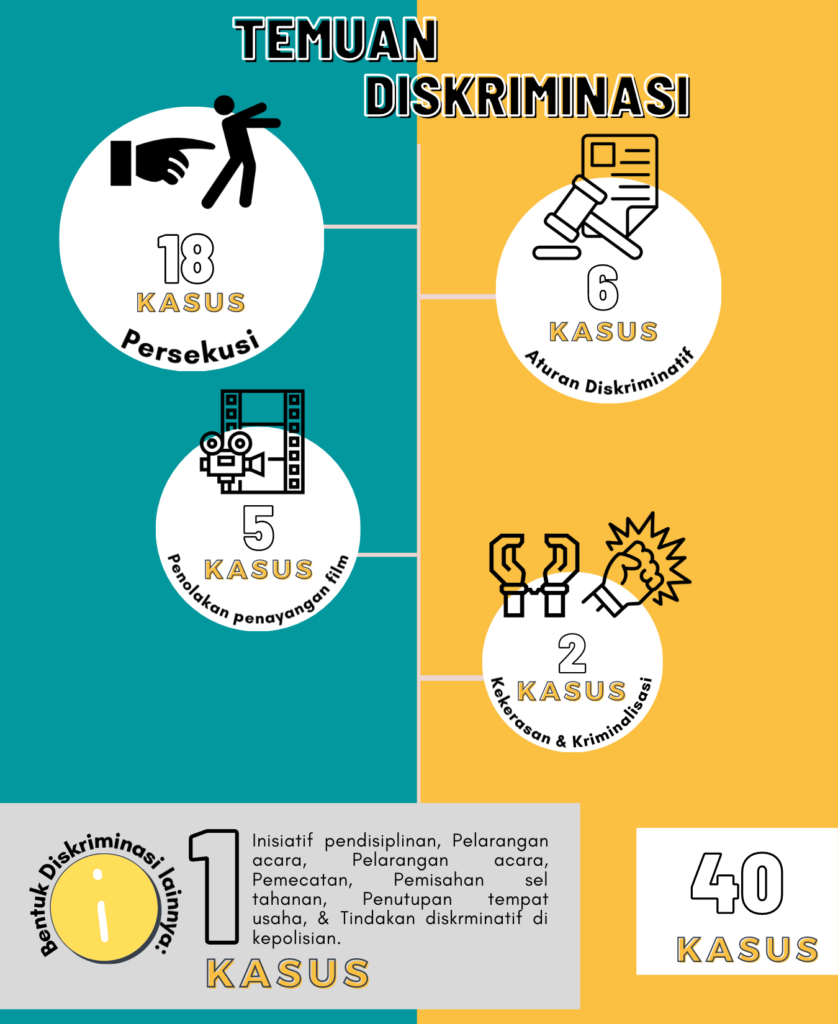Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mengecam sikap pemerintah dan parlemen Gorontalo dalam membuat Surat Edaran yang melarang keterlibatan waria (transpuan) dalam acara hiburan, pesta, karaoke, dan turnamen pertandingan. Surat Edaran ini kontradiktif dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang yang aman bagi semua penduduk untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik, terlepas dari identitasnya.
Pada hari Selasa, 22 April 2025, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil dari forum ini kemudian disahkan ke dalam Surat Edaran Nomor 800/BKBP/76/IV/2025 Tentang Larangan Kegiatan Keramaian Hiburan Rakyat dan Hajatan Pesta yang Melibatkan Waria, Biduan, Alkohol, Narkoba dan Judi yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gorontalo pada tanggal 25 April 2025.
Surat edaran ini menghimbau camat, kepala desa, kepala kelurahan di Gorontalo untuk selektif memberikan izin keramaian pada acara hiburan rakyat, usaha karaoke, turnamen pertandingan, dan hajatan pesta. Poin ketiga dalam surat edaran ini mendesak aparat pemerintah setempat memantau dan mencegah acara keramaian yang melibatkan waria (transpuan).
Para pejabat pemerintahan dan anggota parlemen lokal ikut menyuarakan dukungan atas konten surat edaran ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyatakan bahwa hampir seluruh daerah di Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo, sudah sepakat menolak kehadiran dan aktivitas komunitas tersebut. Pelarangan ini, menurutnya, karena ‘kegiatan waria’ merusak moral bangsa. Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo, Rivai Bukusu, juga mengatakan bahwa mereka menolak kegiatan-kegiatan yang melibatkan transpuan atau komunitas LGBT lainnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.
Atas situasi ini, LBHM memandang ada sesat pikir dan akar stigmatif dari penerbitan surat edaran ini dan juga pernyataan-pernyataan yang turut mendukungnya. Ada setidaknya empat poin mengapa surat edaran ini bermasalah:
Pertama, surat edaran ini melegitimasi marginalisasi dan diskriminasi transpuan di ruang-ruang publik. Surat edaran ini tidak menjelaskan pelibatan waria seperti apa yang dilarang atau dianggap berbahaya. Akibatnya, bukan hanya sebagai penampil (performer), transpuan yang menghadiri acara tersebut sebagai peserta atau penonton pun bisa dianggap terlibat dalam kegiatan tersebut dan akhirnya acara tersebut harus dibatasi. Ini akan membuat kelompok masyarakat menolak kehadiran transpuan secara total dalam kegiatan-kegiatan mereka karena takut acara mereka akan dibatalkan.
Diskriminasi semacam ini bertentangan dengan hak kebebasan berkumpul (freedom to assembly) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Lebih jauh lagi, Pasal 24 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga sudah menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.” Hak ini diberikan tanpa ada distingsi atas identitas gender seseorang, tidak peduli apakah dia laki-laki, perempuan, transpuan, atau identitas gender lain. Keikutsertaan transpuan dalam acara-acara publik dan sipil seperti pertandingan olahraga dan acara kesenian adalah cara mereka melaksanakan kemerdekaan berkumpul.
Kedua, tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui surat edaran tersebut tidak berlandaskan hukum. Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya adalah setiap perbuatan yang hendak atau sedang dilakukan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah harus memiliki landasan hukum serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Memiliki identitas sebagai transpuan bukan sebuah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Di samping itu, pelarangan transpuan untuk berpartisipasi atau menikmati hak untuk berkumpul, berserikat, dan berekspresi melalui Surat Edaran ini menunjukkan kebijakan yang dibuat bersifat subjektif tanpa ada landasan hukum mengapa kehadiran transpuan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dilarang. Pola-pola legislasi serampangan tanpa ada dasar hukum yang jelas ini berisiko memprovokasi kebencian terhadap kelompok transpuan dan bahkan dapat mengarah pada eigenrichting (main hakim sendiri). Apalagi kelompok transpuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebab masyarakat lebih mudah mengidentifikasi berdasarkan ekspresi gendernya.
Ketiga, pelarangan transpuan untuk hadir di kegiatan-kegiatan hiburan melanggar tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak atas pekerjaan bagi warganya. Menurut sebuah survei, sekitar 8.7% anggota komunitas LGBTIQ+ berprofesi di sektor hiburan, seperti pengamen jalanan ataupun artis (penyanyi, penyanyi lip sinc, penari, dan lain-lain). Mereka yang bekerja sebagai pekerja informal ini menghadapi berbagai risiko ekonomi dan seringkali tidak mendapatkan jaminan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu urusan wajib dari Pemerintah Daerah adalah memberikan lapangan kerja yang aksesibel bagi semua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah dan DPRD Gorontalo seharusnya bisa melindungi hak pekerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia, tidak terkecuali pekerja seni informal, bukan malah melarang transpuan untuk bekerja sebagai pekerja seni dan pertunjukkan.
Ada alasan mengapa banyak transpuan bekerja di sektor informal, karena mereka kerap kali sudah tersingkir dan terdiskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan formal. Ketimbang memberikan solusi atas diskriminasi hak atas pekerjaan yang selama ini sudah dialami oleh transpuan, surat edaran pemerintah Kabupaten Gorontalo ini semakin menyudutkan kelompok transpuan.
Keempat, alasan penolakan transpuan di kegiatan-kegiatan hiburan mengulang kembali alasan usang tentang transpuan melanggar norma kesusilaan. Bahkan ada simplifikasi argumen bahwa transpuan yang melakukan pekerjaan seni sudah pasti orang yang tidak beragama dan tidak bermoral. Dalam keterangannya Adhan Dambea, Walikota Gorontalo, menyatakan, “Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo, untuk jangan mengundang penyanyi seperti waria. Di Kota Gorontalo masih banyak penyanyi-penyanyi yang bermoral dan punya agama.”
Padahal beberapa budaya lokal Indonesia juga mengakui keberadaan gender lain, seperti budaya Bugis yang mengenal lima jenis kelamin yang berbeda. Ada pula interpretasi-interpretasi ajaran keagamaan yang memberikan pandangan yang lebih toleran bagi individu trans. Otoritas kesehatan internasional seperti WHO dan nasional seperti Kementerian Kesehatan pun berulang kali menyatakan bahwa menjadi transpuan bukanlah sebuah gangguan kejiwaan.
“Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Surat Edaran ini tidak mencerminkan visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo. Padahal poin pertama dari Asta Cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Maka praktik diskriminasi seperti ini tidak seharusnya dibiarkan menjamur atau bahkan dilegitimasi karena justru menghambat terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, ucap Novia Puspitasari, Koordinator Riset dan Program LBHM.
Dari poin-poin di atas, LBHM mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk mencabut Surat Edaran Nomor 800/BKBP/76/IV/2025 Tentang Larangan Kegiatan Keramaian Hiburan Rakyat dan Hajatan Pesta yang Melibatkan Waria, Biduan, Alkohol, Narkoba dan Judi. Kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten dan Kota Gorontalo untuk menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk menjaga dan melindungi hak kelompok rentan, tak terkecuali transpuan.
Selain itu, LBHM juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan aturan yang lebih atas untuk mengevaluasi surat edaran ini. LBHM juga berpendapat bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai pihak yang melakukan pengawasan atas praktik dan kebijakan yang berdampak negatif pada pemenuhan HAM untuk melakukan investigasi pemberangusan hak yang terjadi di Gorontalo pada kelompok transpuan.
Jakarta, 30 April 2025
Narahubung:
Novia – 081297566190
Referensi
Arief Rahadian, Gabriella Devi Benedicta, Fatimah Az Zahro, Kelompok Keragaman Seksual dan Gender di Tengah Pusaran Pandemi: Antara Kerentanan dan Resiliensi, Studi Dampak COVID-19 terhadap Situasi Sosial, Ekonomi, dan Hukum Kelompok Keragaman Seksual dan Gender di Indonesia, (Jakarta: Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), 2021).
Daniel Stables, “Mengenal lima gender dalam Suku Bugis di Sulawesi yang kerap alami stigma dan diskriminasi, ‘Di masa depan, bissu akan terancam punah’,” bbc.com, 25 April 2021, diakses di https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-56854166