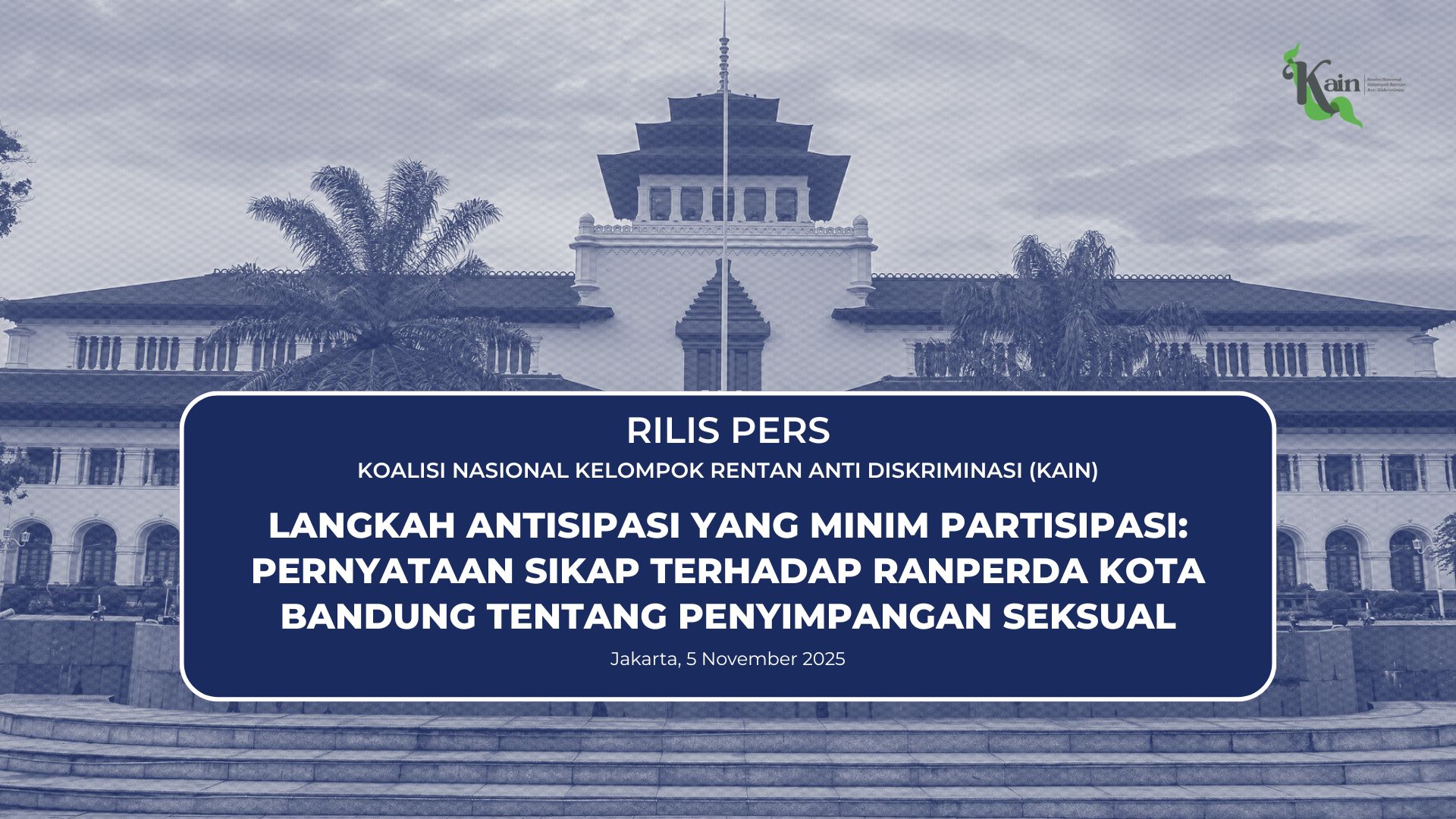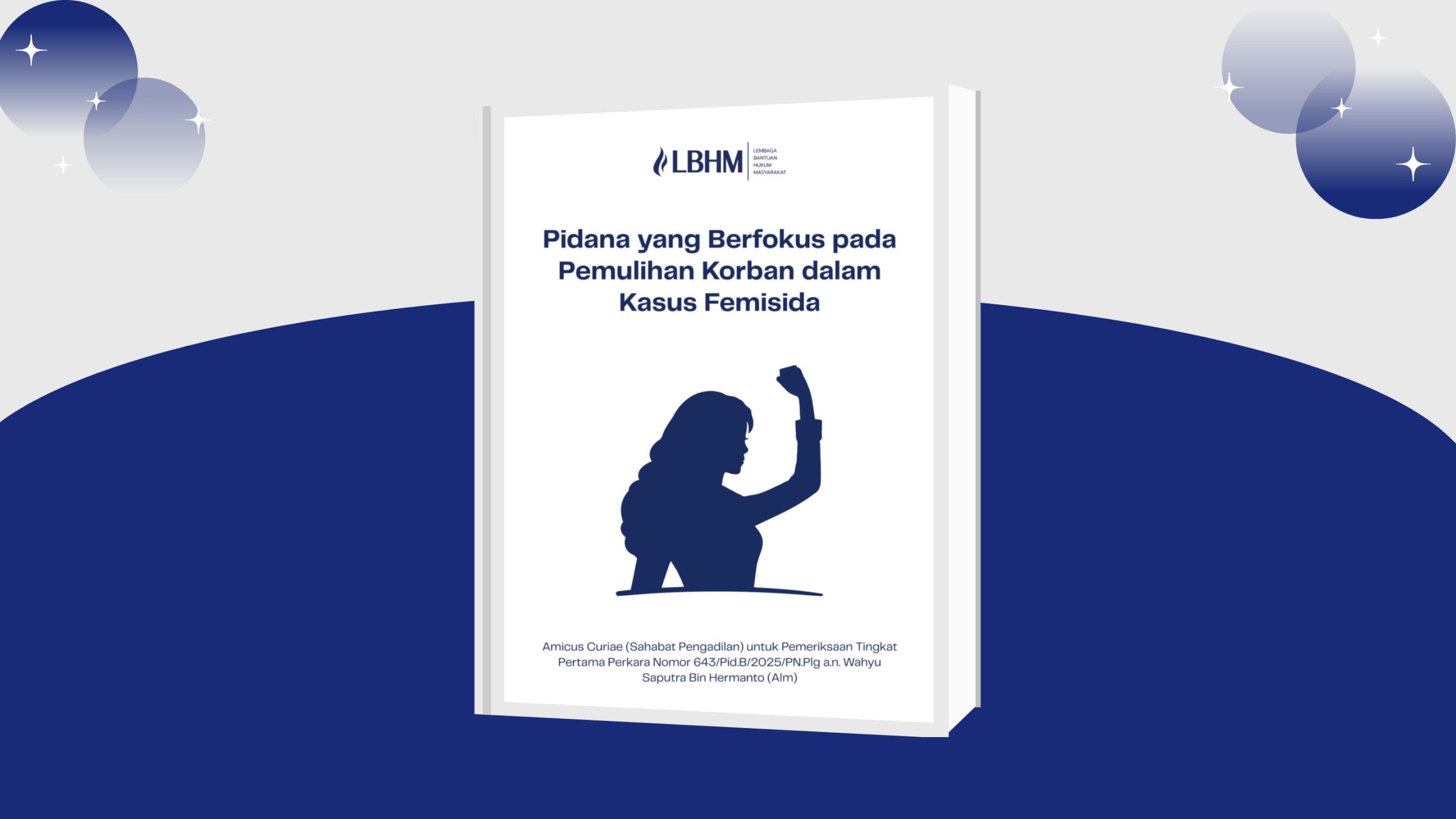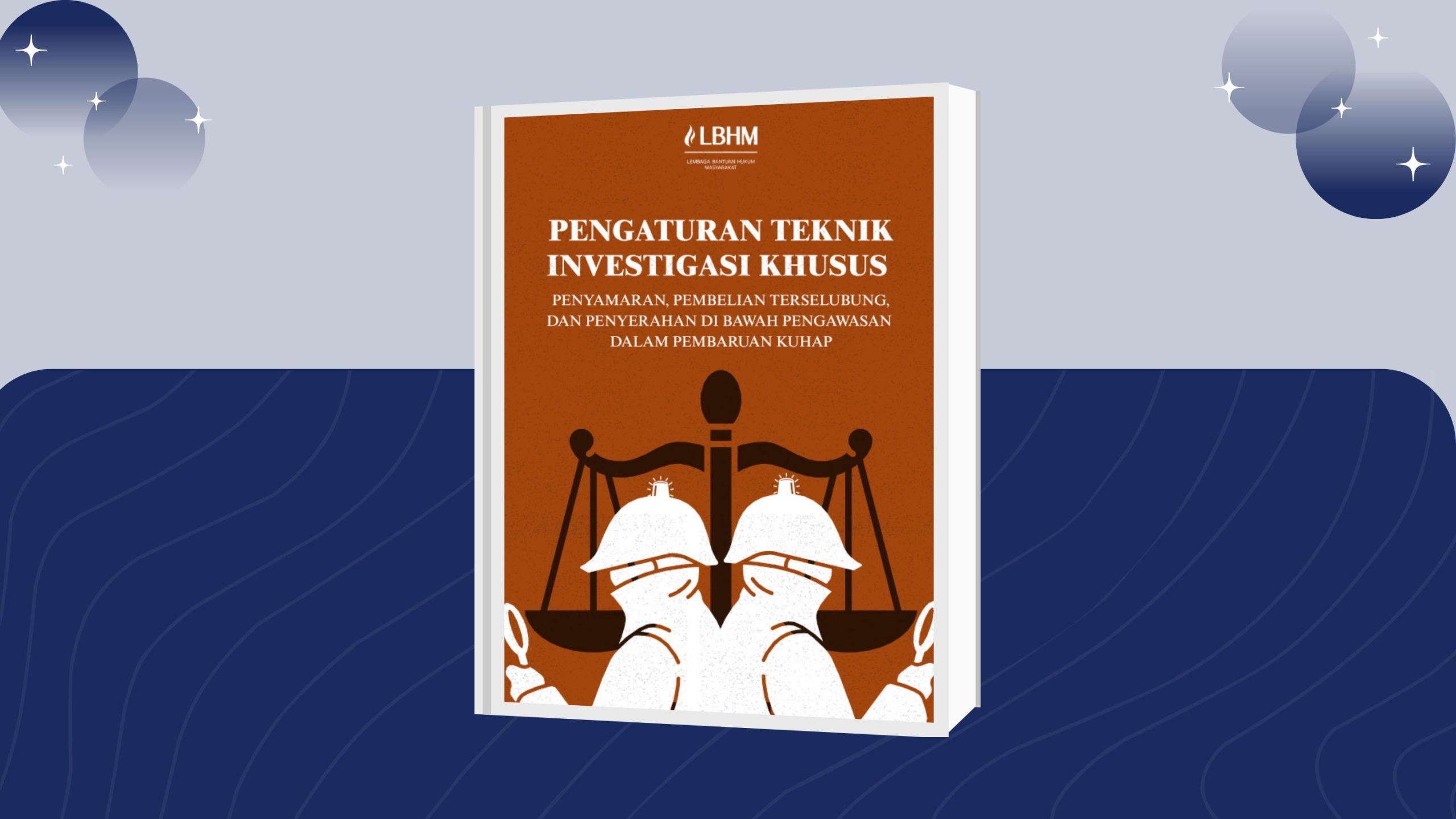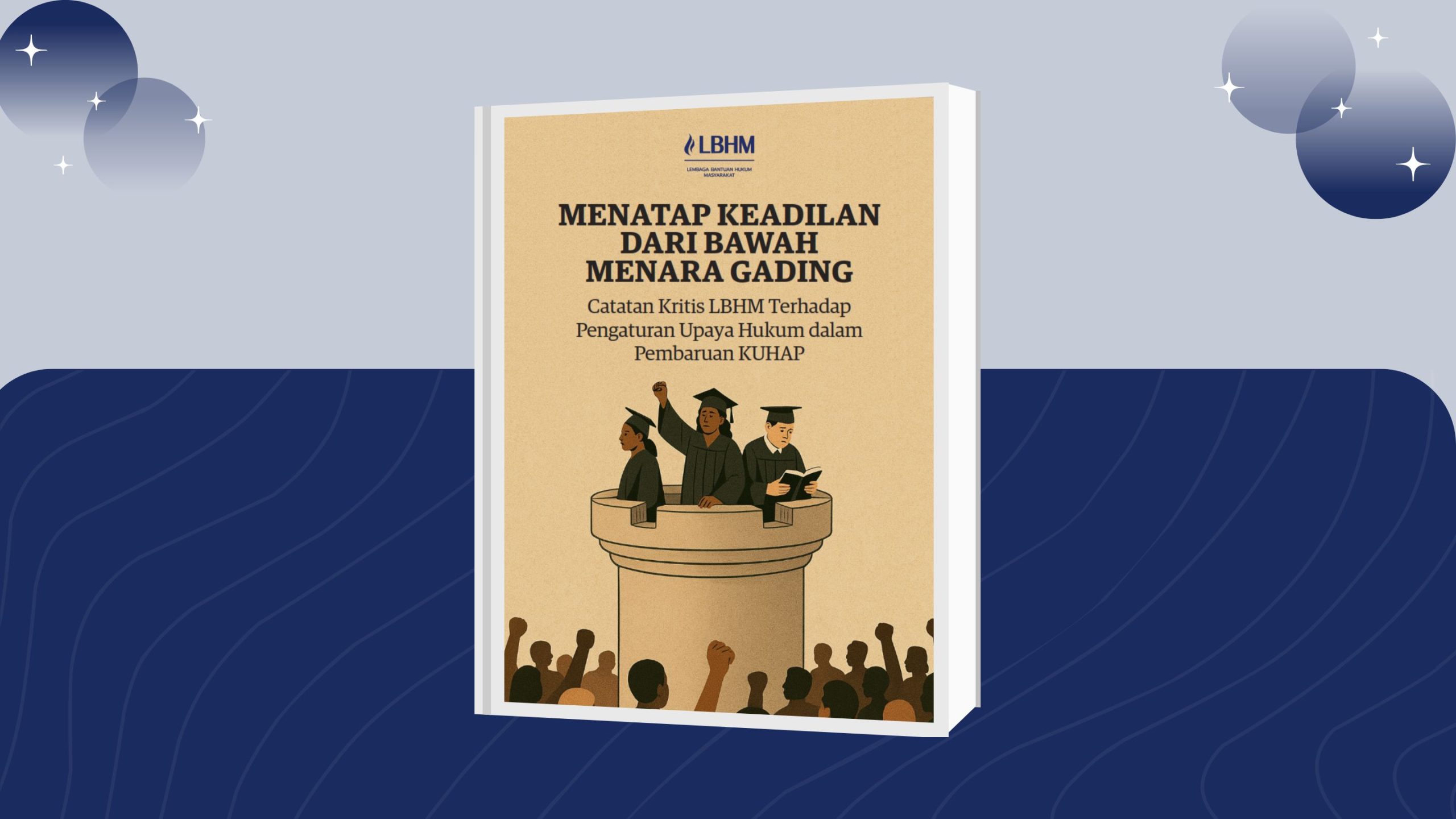Peringatan Darurat: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP
Pada Kamis, 13 November 2025, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara telah selesai melakukan Pembahasan RUU KUHAP dan melakukan pengambilan keputusan Tingkat I hanya dalam waktu dua hari.
Artinya RUU KUHAP ini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menunggu sidang paripurna yang rencananya akan dijadwalkan Minggu depan.
Selama pembahasan RUU KUHAP ini, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai terdapat tumpukan masalah dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan. Proses pembahasan nampak terburu-buru untuk mengejar pengesahan KUHAP agar dapat berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026.
Terlebih surat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP perihal permohonan respons atas masukan selama Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) maupun masukan tertulis yang disampaikan langsung, luput direspons bahkan dipertimbangkan dan diakomodir dalam pembahasan RUU KUHAP.
Pada sisi lain dari aspek substansi, pasal-pasal dalam RUU KUHAP yang sudah disetujui di tingkat I ini memuat pasal-pasal bermasalah, pasal karet, dan pasal yang menyuburkan praktik penyalahgunaan wewenang, di antaranya:
Semua Bisa Dijebak Aparat
Operasi undercover buy (pembelian terselubung) & controlled delivery (pengiriman di bawah pengawasan) yang sebelumnya menjadi kewenangan penyidikan dan hanya untuk tindak pidana khusus yakni narkotika. Dalam RUU KUHAP kewenangan ini menjadi metode penyelidikan (menciptakan tindak pidana), dan bisa diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, tidak punya batasan dan tidak diawasi hakim (Pasal 16).
Kewenangan luas tanpa pengawasan ini berpotensi membuka peluang penjebakan (entrapment) oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan tindak pidana dan merekayasa siapa pelakunya yang memang menjadi tujuan tahap penyelidikan itu sendiri untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.
Semua Bisa Kena Diamankan, Ditangkap, dan Ditahan Tanpa Kejelasan, Bahkan di Tahap Penyelidikan Saat Belum Ada Tindak Pidana
Semua bisa kena melalui pasal karet dengan dalih mengamankan khususnya pada tahap penyelidikan yang belum terkonfirmasi ada tidaknya tindak pidana (Pasal 5). Bahkan, jika dibandingkan dengan Pasal 5 KUHAP existing, tindakan yang bisa dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, tidak sama sekali diperbolehkan untuk melakukan penahanan.
Namun dalam Pasal 5 RUU KUHAP, pada tahap penyelidikan, dapat dilakukan Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan bahkan Penahanan, padahal pada tahap ini tindak pidana belum terkonfirmasi.
Semua Bisa Kena Tangkap-Tahan Sewenang-Wenang Tanpa Izin Hakim
Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan sebagaimana saat ini membuka lebar ruang kesewenang-wenangan aparat karena tidak ada pengawasan oleh lembaga pengadilan melalui pemeriksaan habeas corpus, serta penyimpangan aturan mengenai masa penangkapan yang terlalu panjang (lebih dari 1×24 jam) dalam undang-undang sektoral di luar KUHAP juga tidak diperbaiki dalam RUU KUHAP (Pasal 90, 93).
Semua Bisa Kena Geledah, Sita, Sadap, dan Blokir Menurut Subjektivitas Aparat Tanpa Izin Hakim
Pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dengan alasan subjektif aparat (Pasal 105, 112A, 132A). RUU KUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa izin hakim dengan dilandaskan pada undang-undang yang bahkan belum terbentuk (Pasal 124).
Semua Bisa Kena Peras dan Dipaksa Damai dengan Dalih “RJ”, Bahkan di Ruang Gelap Penyelidikan
Dalam Pasal 74a RUU KUHAP dijelaskan bahwa kesepakatan damai antara pelaku dan korban dapat dilaksanakan pada tahapan belum terdapat tindak pidana (penyelidikan). Hal ini sangat dipertanyakan, bagaimana mungkin belum ada tindak pidana namun sudah ada subjek pelaku dan korban?
Selain itu hasil kesepakatan damai yang ditetapkan oleh pengadilan hanya surat penghentian penyidikan, sedangkan penghentian penyelidikan sama sekali tidak dilaporkan ke otoritas manapun, ini menjadi ruang gelap di penyelidikan.
RUU KUHAP gagal menjamin sistem check and balance oleh pengadilan dalam mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) karena penetapan hakim untuk penghentian penyidikan hanya akan dianggap stempel, tanpa memandatkan kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan secara substansial (judicial scrutiny) dan memberikan opsi menolak untuk menetapkan kesepakatan RJ yang tidak sesuai ketentuan, termasuk jika ada indikasi pemaksaan, pemerasan, atau penyalahgunaan lainnya oleh aparat (Pasal 78, 79).
Semua Bisa Polisi Kuasai
Semua PPNS dan Penyidik Khusus di letakan di bawah koordinasi Polisi, menjadikan Polri lembaga superpower dengan kontrol sangat besar (Pasal 7 dan Pasal 8). Padahal selama ini masih memiliki beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana.
Semua Penyandang Disabilitas Bisa Tanpa Perlindungan
Pasal-pasal dalam RKUHAP masih bersifat ableistik karena tidak mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses hukum berpotensi berjalan secara tidak setara dan diskriminatif. Lebih jauh, Pasal 137A membuka peluang penghukuman tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, dan secara implisit menempatkan keduanya sebagai pihak tanpa kapasitas hukum.
Pasal ini berpotensi melegitimasi perampasan kemerdekaan dan pengurungan sewenang- wenang (arbitrary detention), karena penjatuhan sanksi tidak diposisikan sebagai putusan pidana sehingga tidak memiliki standar jelas terkait batas waktu, mekanisme pengawasan, maupun penghentian tindakan. Situasi tersebut membuka ruang praktik koersif dengan dalih penegakan hukum.
Semua Bisa Kena, Semua Bisa Jadi Korban, Semua Bisa Direkayasa Jadi Tersangka, dan Semuanya Terjadi karena RKUHAP Dipaksakan Terburu-buru
RUU KUHAP berlaku tanpa masa transisi, langsung mengikat jutaan aparat dan warga tanpa kesiapan infrastruktur dan pengetahuan mulai 2 Januari 2026. Terdapat lebih dari 10 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang akan dikebut dalam waktu setahun (Pasal 332 dan 334).
Artinya, potensi kekacauan praktik KUHAP Baru yang diterapkan tanpa adanya peraturan pelaksana akan sangat nyata terjadi setidaknya selama setahun ke depan. Koalisi juga sudah sering menyoroti bahwa kebutuhan mengakomodir perubahan krusial KUHP Baru ternyata juga belum diatur secara memadai dalam draf terakhir RUU KUHAP yang diputuskan dalam Tingkat I.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menyerukan agar:
- Presiden menarik draf RUU KUHAP per 13 November 2025 untuk tidak dilanjutkan dalam pembahasan Tingkat II sidang paripurna;
- Pemerintah dan DPR merombak substansi draf RUU KUHAP per 13 November 2025 dan membahas ulang arah konsep perubahan KUHAP untuk memperkuat judicial scrutiny dan mekanisme check and balances, sebagaimana usulan konsep-konsep dalam Draf Tandingan RUU KUHAP versi Masyarakat Sipil ; dan
- Pemerintah dan DPR tidak menggunakan alasan yang menyesatkan publik terkait pemberlakuan KUHP Baru semata-mata untuk memburu-buru pengesahan RUU KUHAP yang masih sangat bermasalah.
Jakarta, 14 November 2025
-Hormat kami,
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP