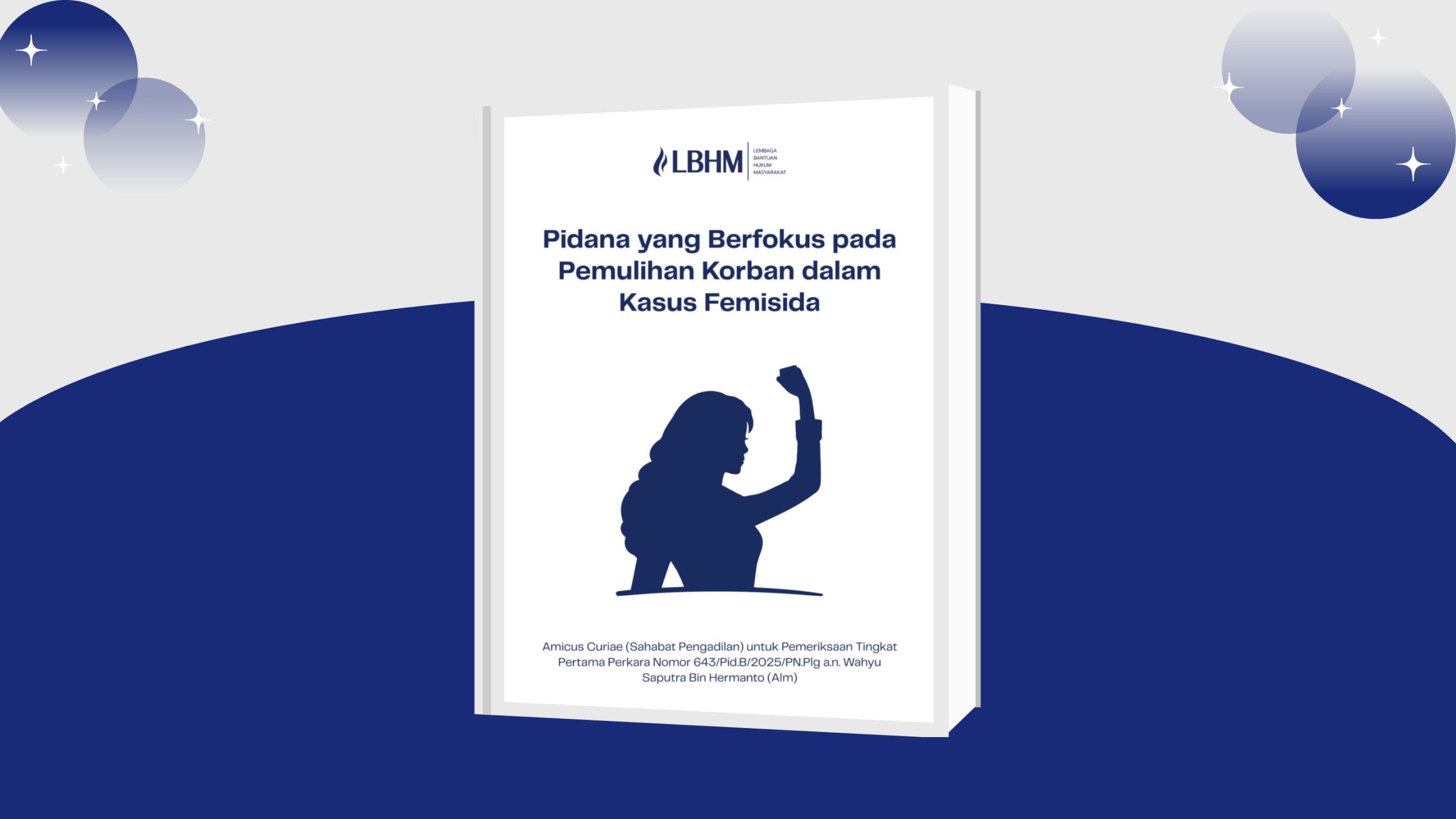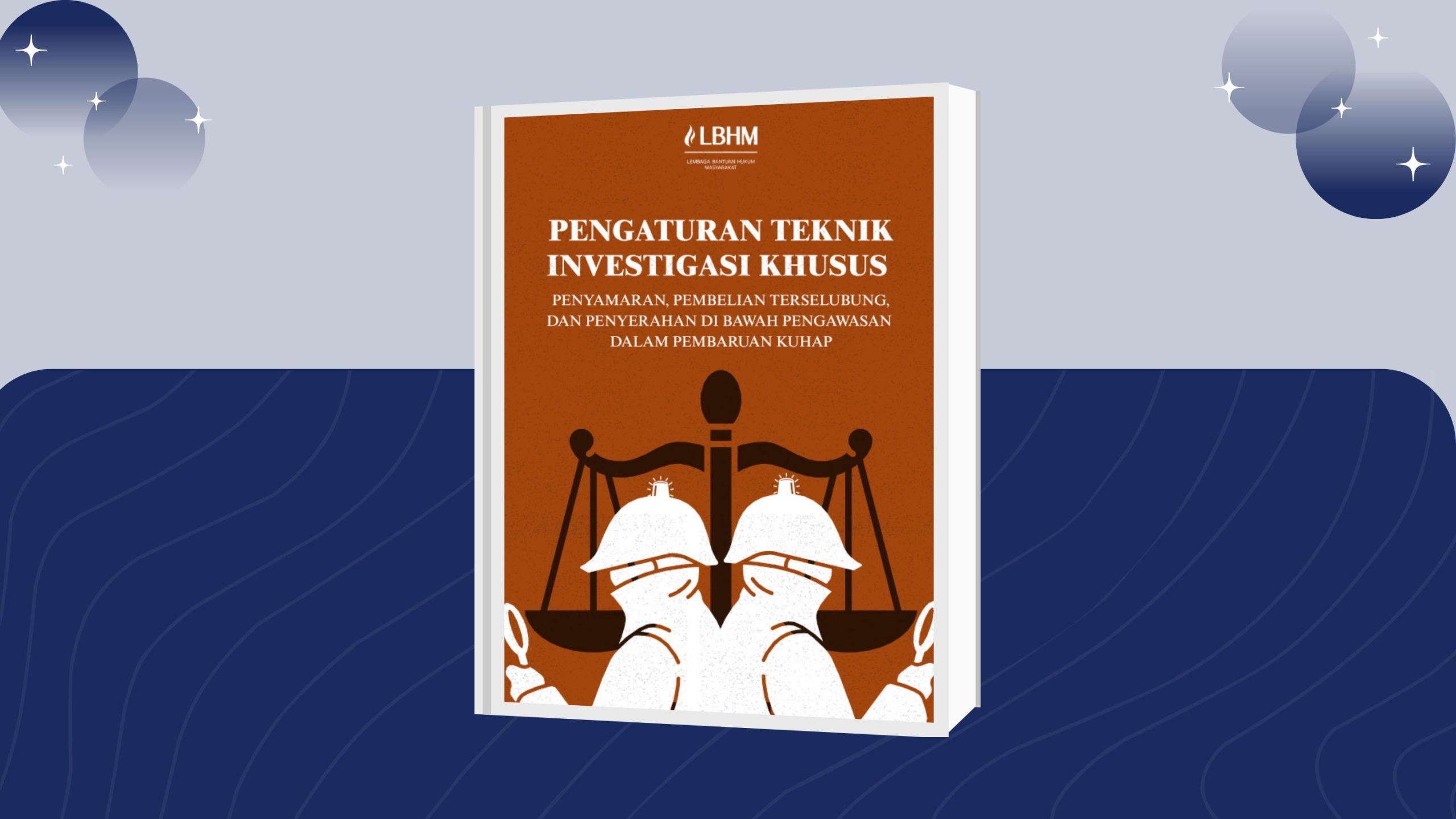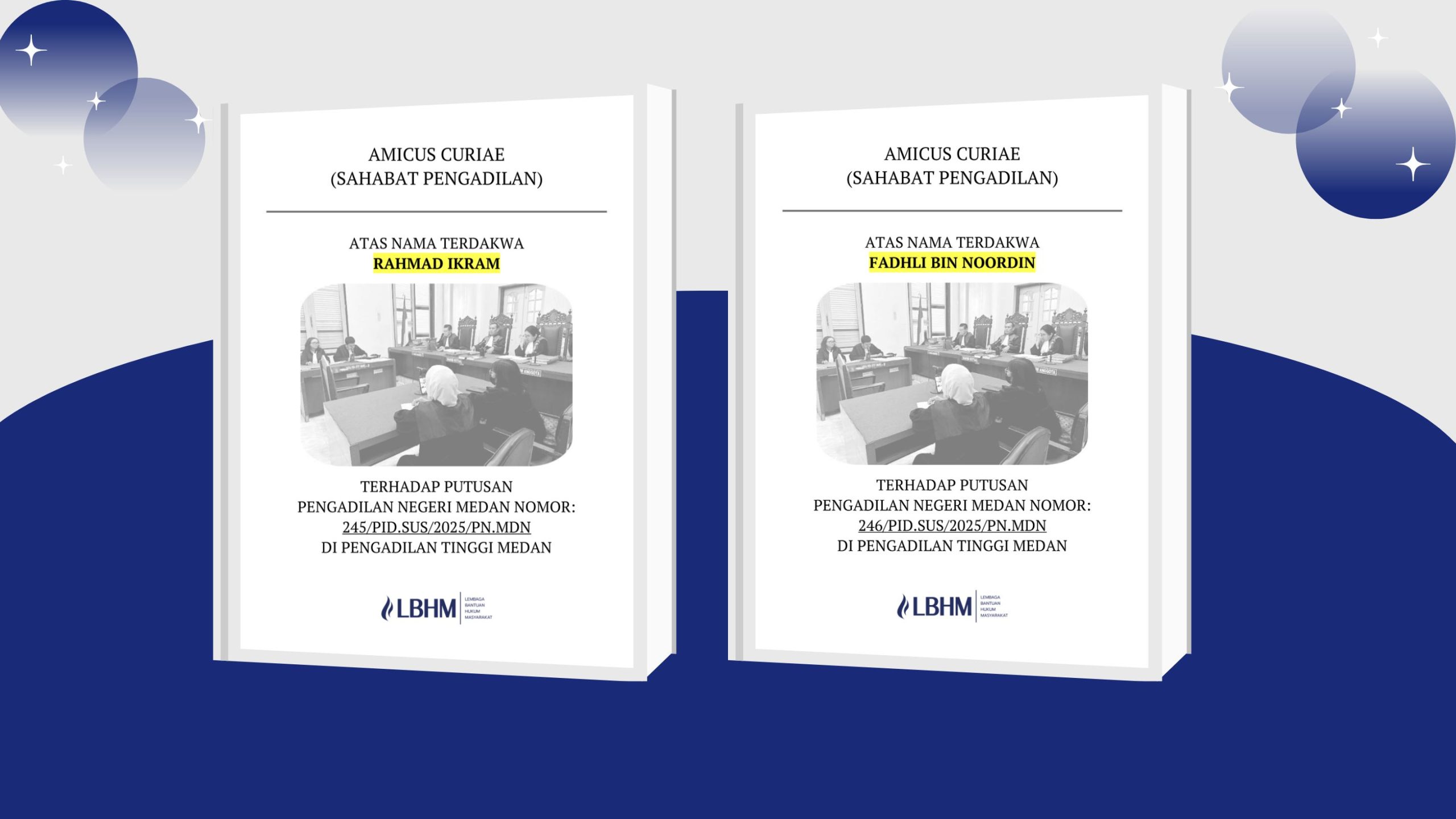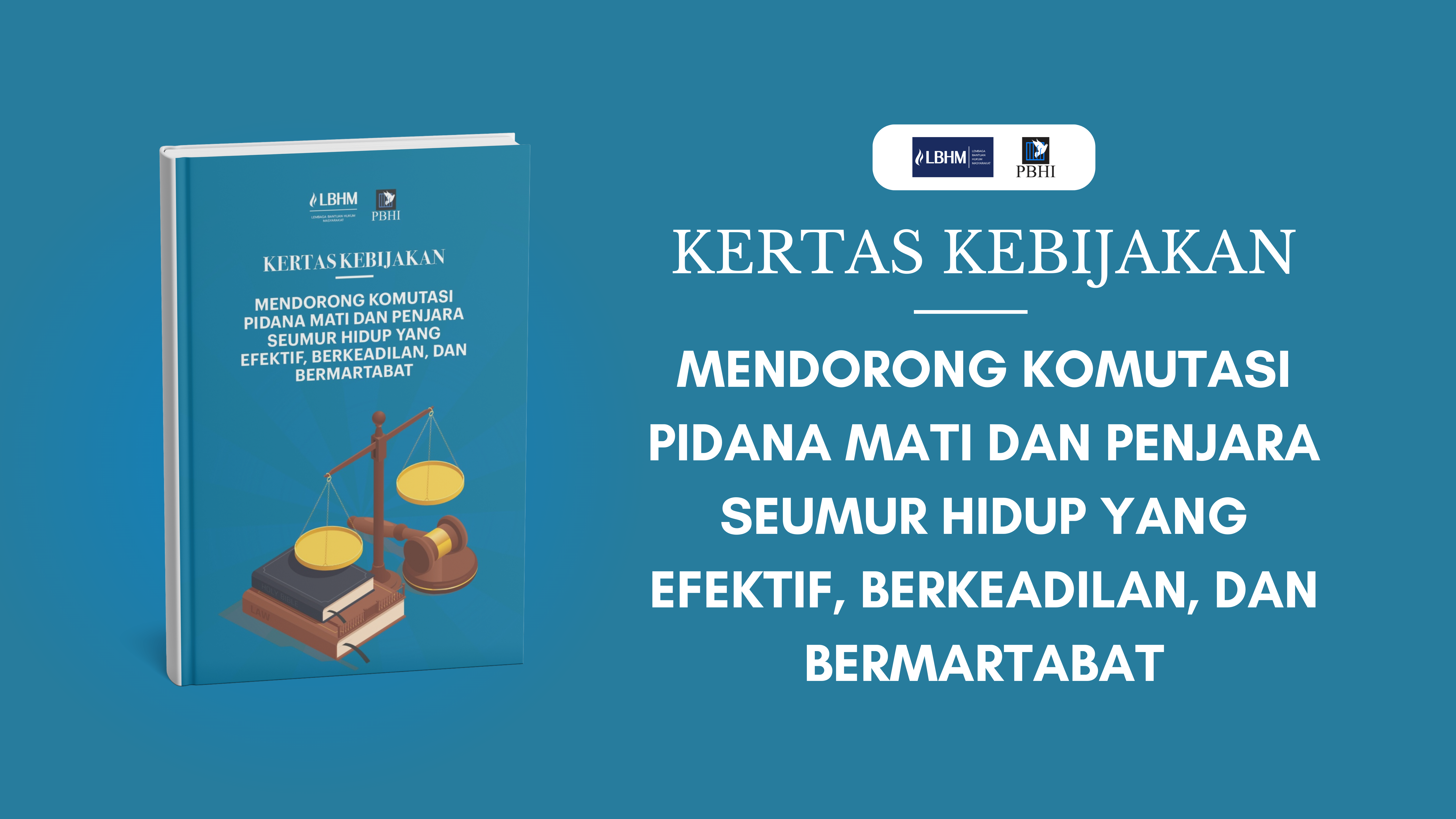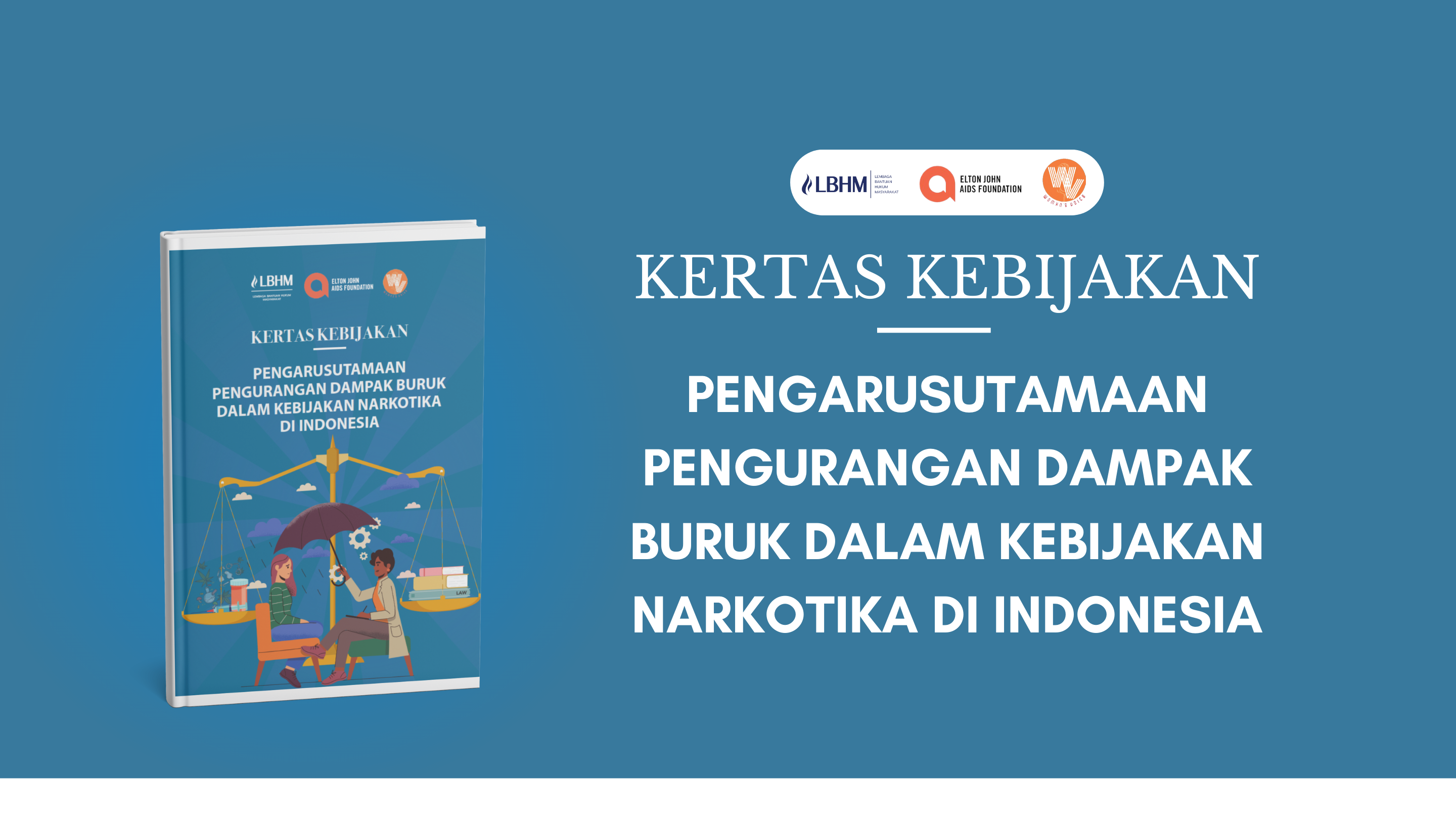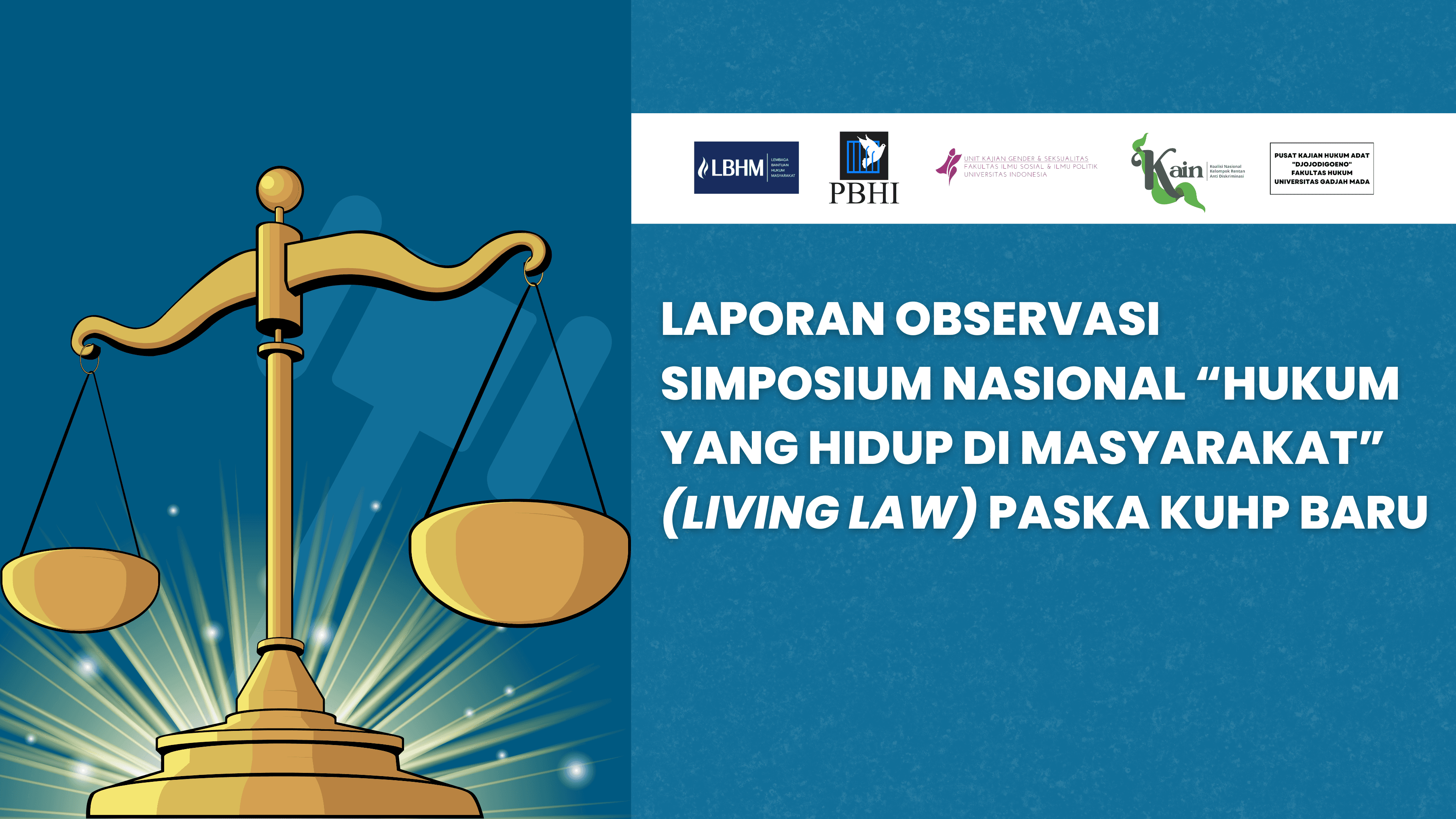Amicus Curiae Wahyu Saputra – Pidana yang Berfokus pada Pemulihan Korban dalam Kasus Femisida
Awal 2025, publik diguncang kasus tragis Sindi Purnama Sari, perempuan hamil tiga bulan yang disekap, diabaikan kesehatannya, dan mengalami kekerasan oleh suaminya sendiri, Wahyu Saputra. Setelah berbulan-bulan tersiksa, Sindi meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Palembang.
Jaksa menuntut hukuman mati bagi Wahyu. Namun, kasus ini lebih dari sekadar kejahatan individual ini adalah bentuk femisida, pembunuhan terhadap perempuan yang berakar dari budaya patriarki dan sistem sosial yang gagal melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Hukuman Mati Bukan Solusi
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah menegaskan bahwa pidana mati bukan lagi hukuman pokok, melainkan alternatif terakhir. Hukuman mati bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan hak asasi manusia, serta tren global di mana lebih dari 100 negara telah menghapus hukuman mati.
Penjatuhan pidana mati dalam kasus ini tidak menyentuh akar masalah femisida. Ia justru menutup peluang refleksi dan perubahan sistem yang membuat kekerasan terhadap perempuan terus berulang.
Fokus pada Pemulihan
Fokus penghukuman seharusnya bukan pada balas dendam, melainkan pemulihan bagi korban dan keluarganya. Anak korban, AS, kini hidup dalam trauma dan berpotensi kehilangan kedua orang tuanya. Sistem hukum harus memastikan haknya atas restitusi dan perlindungan, bukan memperparah penderitaannya melalui hukuman mati pada ayahnya.
Kasus ini mengingatkan kita: keadilan sejati bukan tentang menghilangkan nyawa, tapi memulihkan kemanusiaan.
Simak amicus selengkapnya melalui link di bawah ini: