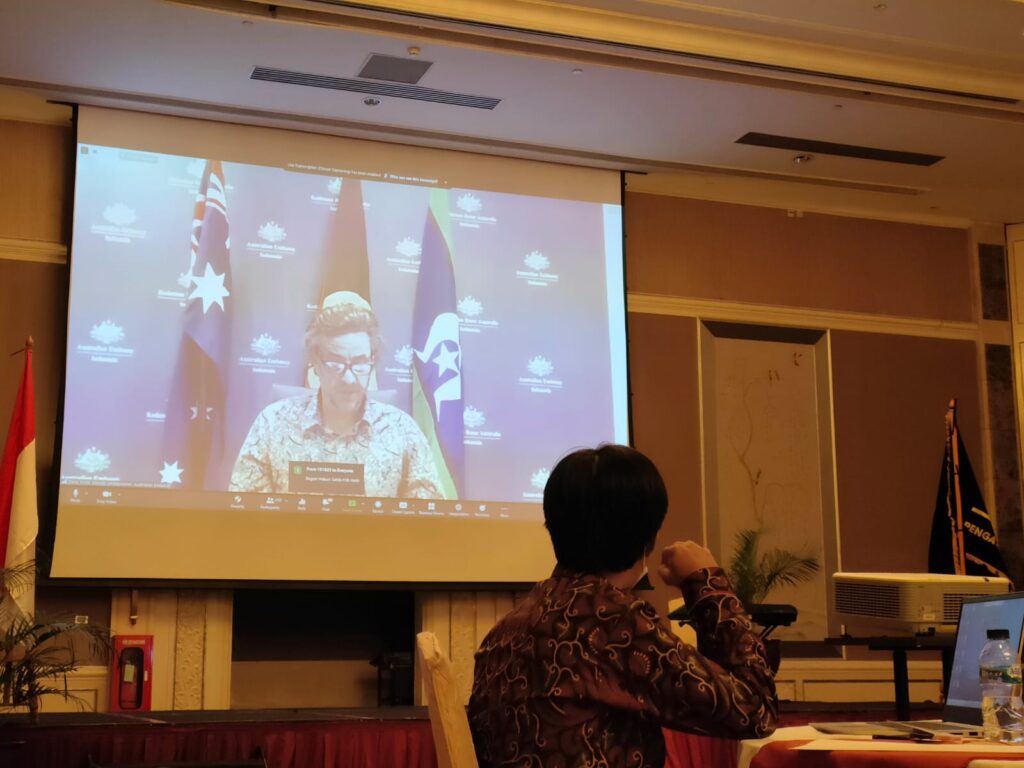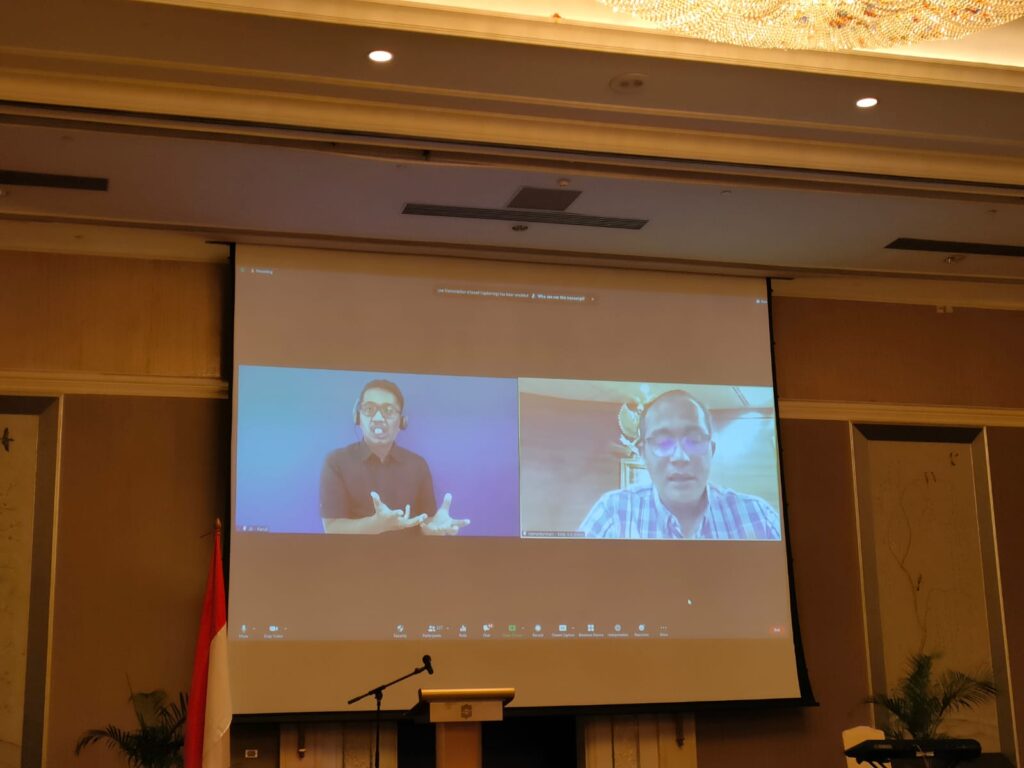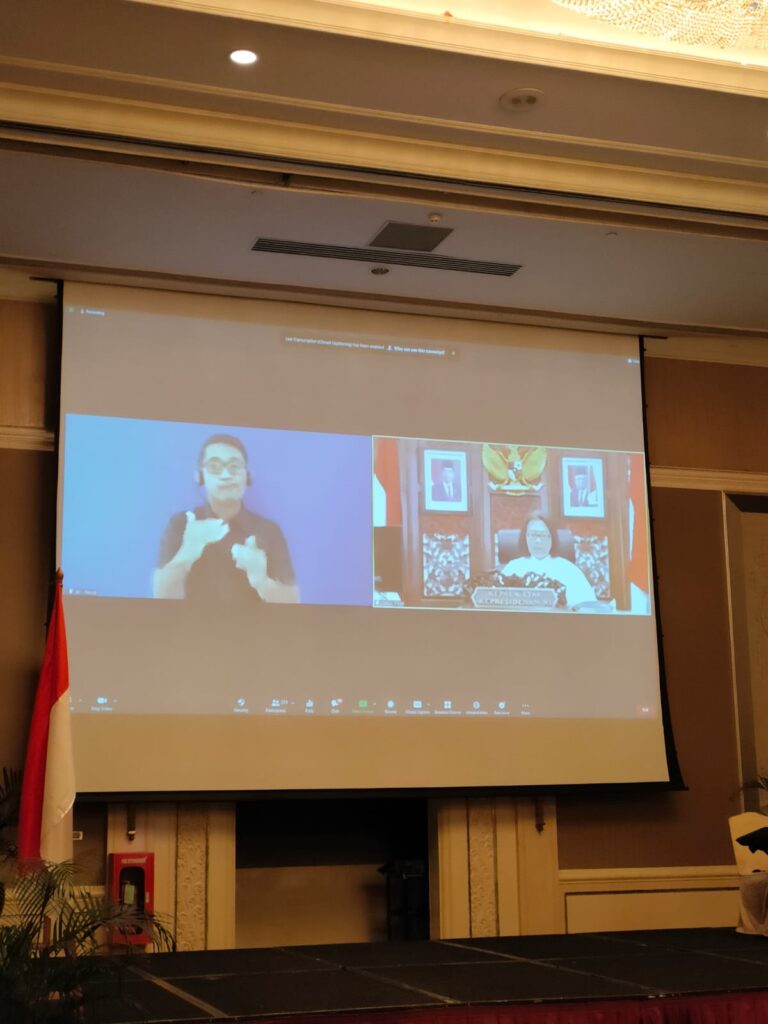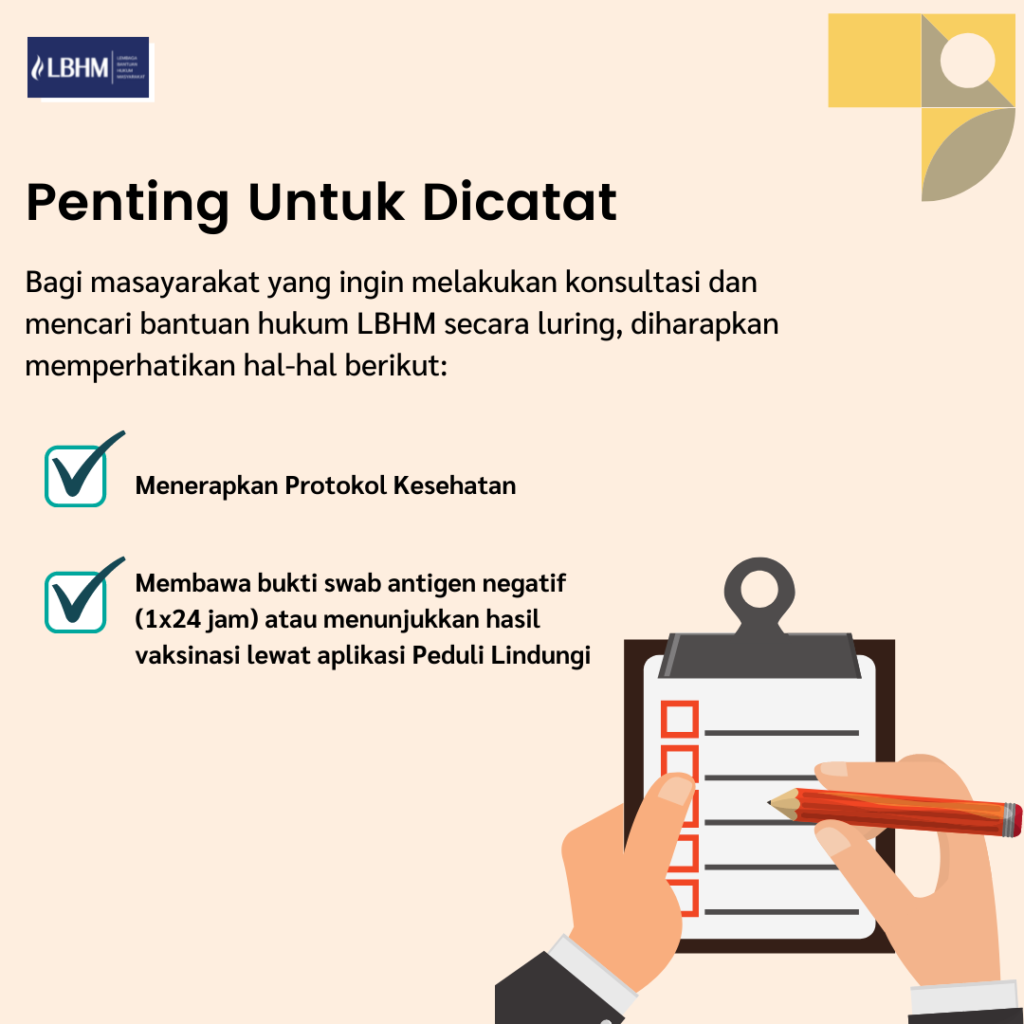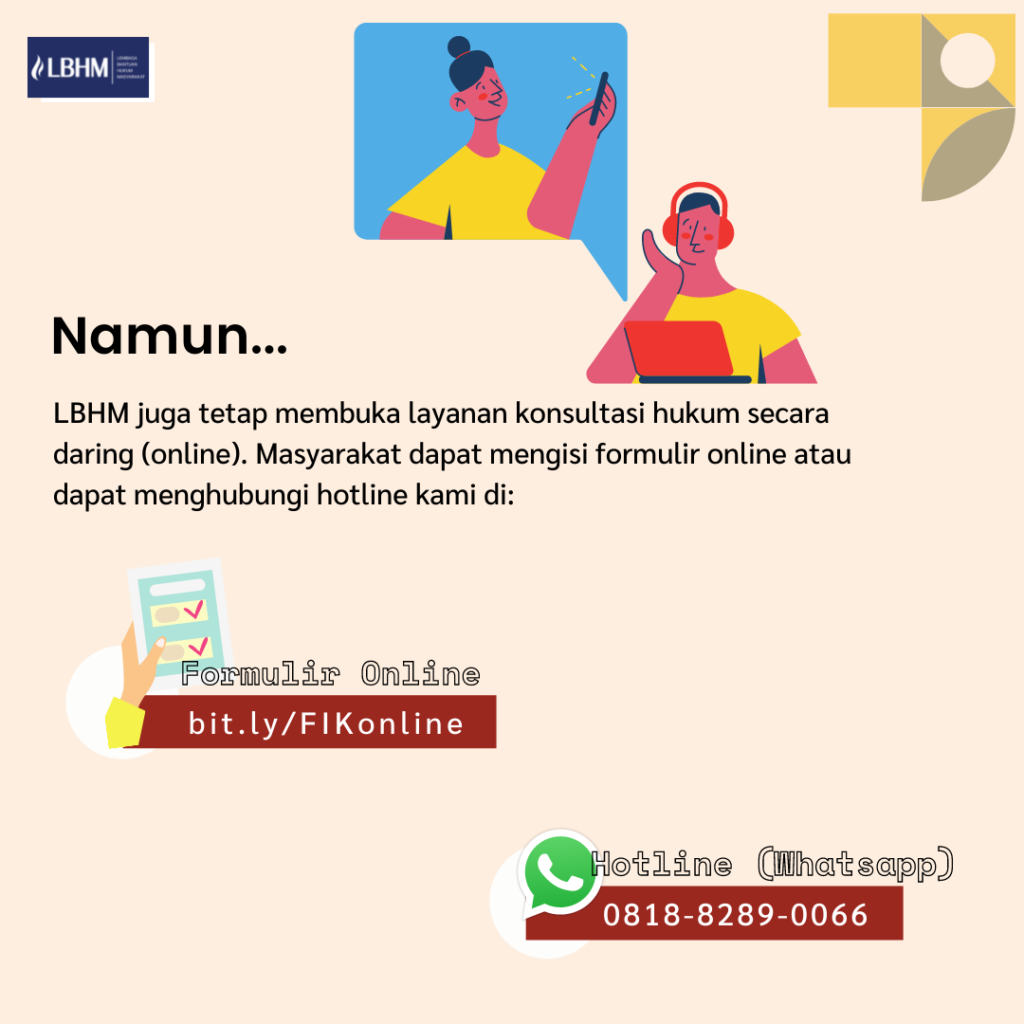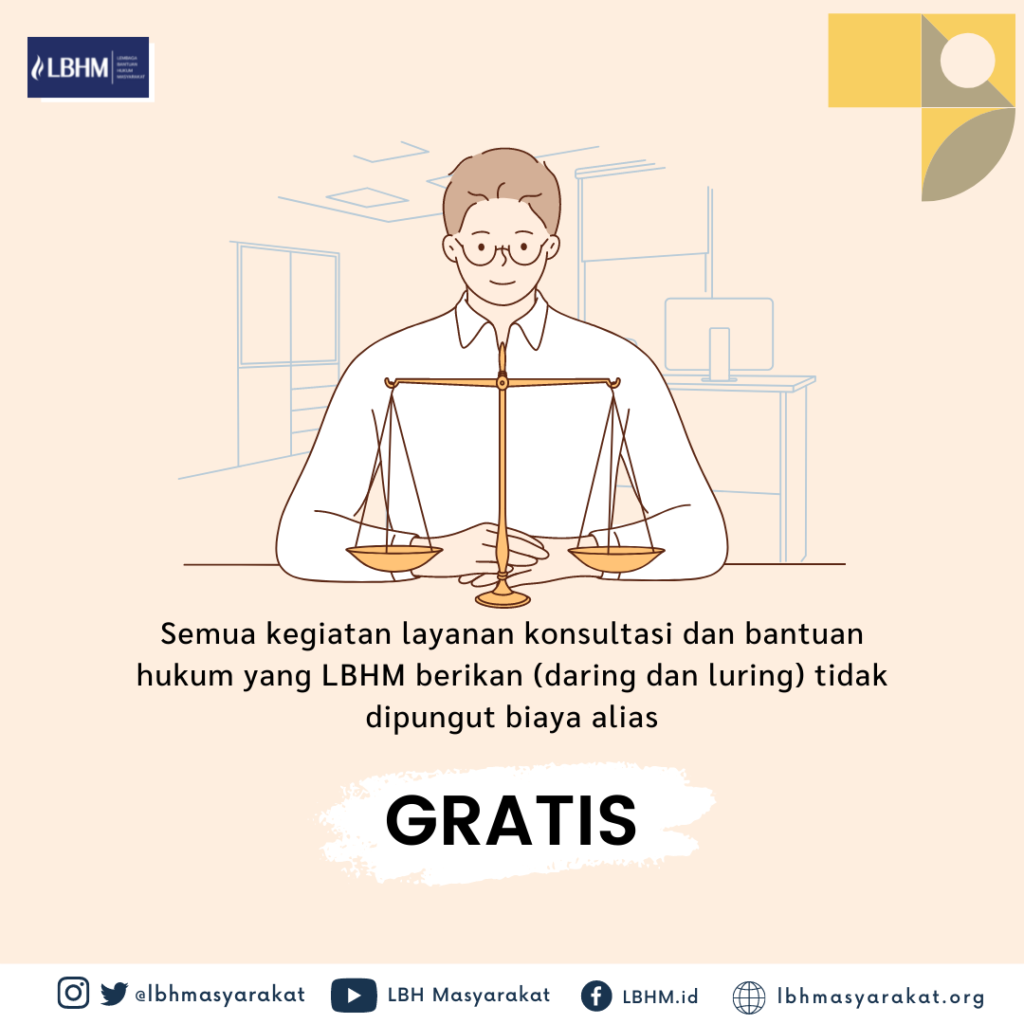Kerangkeng Bupati Langkat: Bukti Suburnya Praktik Rehabilitasi Liar
Oleh LBH Masyarakat (LBHM) & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Jakarta, 25 Januari 2022 – Penangkapan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas kasus korupsi, yang diikuti dengan penemuan kerangkeng besi yang diduga digunakan sang koruptor untuk mengurung pekerja yang menggarap sawitnya, turut menguak dugaan praktik perbudakan.
Jeruji besi tersebut diketahui sudah ada sejak 2012, dan dikatakan hendak digunakan sebagai tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika meski tidak layak secara fasilitas. Pemberitaan menyebutkan bahwa pada 2017 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat sempat meminta Terbit mengurus perizinan jika hendak menjadikan ruangan tersebut sebagai tempat rehabilitasi. Namun, hingga kini tempat tersebut dilaporkan tidak berizin.
Publik patut menduga jika alibi fasilitas rehabilitasi ini hanya jadi alasan untuk menutupi dugaan perbudakan yang terjadi. Penempatan manusia ke dalam kerangkeng seperti yang dilakukan Terbit jelas telah merampas kemerdekaan seseorang untuk bergerak, yang hanya bisa dilakukan oleh otoritas berwenang dan dengan dasar putusan pengadilan. Masalah ini pun tidak bisa dikecilkan sebatas masalah legalitas perizinan. Jika pun benar digunakan sebagai panti rehabilitasi, hal ini tidak lantas menghapuskan pelanggaran berat yang dilakukan, sekalipun dengan dalih untuk membantu orang-orang yang mengalami adiksi. Konsep panti rehabilitasi bukan penjara, dan tidak bisa dipersamakan dengan penjara.
Kecenderungan menggunakan pendekatan pemidanaan terhadap pengguna narkotika hanya akan menciptakan ruang-ruang korupsi yang masif, tak terkecuali pada proses rehabilitasi. Banyak pengguna narkotika yang diserahkan begitu saja pada tempat-tempat rehabilitasi tanpa asesmen mengenai adiksinya. Beberapa orang yang tertangkap namun tidak memiliki bukti, tetap dipaksa direhabilitasi hanya karena memiliki urine positif, serta kerap dimintai sejumlah uang. Padahal secara medis tidak semua pengguna narkotika perlu direhabilitasi.
Kondisi ini memikul segudang masalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius di samping dugaan praktik perbudakan. Ditinjau dari aspek kewenangan, otoritas yang oleh hukum dapat melakukan perampasan kemerdekaan seseorang hanya aparat penegak hukum, bukan Bupati. Tindakan perampasan kemerdekaan itu bahkan dapat dijerat dengan Pasal 333 ayat 1 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun”. Bahkan hukuman atas perbuatan tersebut dapat diperperberat jika ditemukan luka berat bagi orang yang dirampas kemerdekaannya.
Meskipun alasan Bupati Terbit adalah terkait rehabilitasi narkotika, justru tindakan tersebut menambah satu persoalan lagi mengenai pelanggaran aspek prosedur operasional dan legalitas, yang dapat diancam pidana dengan Undang-Undang tentang Kesehatan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Ditemukannya tempat rehabilitasi ilegal di kediaman Bupati Langkat, justru meneguhkan temuan lapangan dalam kasus-kasus narkotika. Pertama, bagi seorang pecandu yang ditangkap aparat banyak yang dikirim ke tempat-tempat rehabilitasi bukan dalam skema proses hukum. Praktik ini dikategorikan sebagai penahanan sewenang-wenang. Sebab seseorang ditahan tanpa diputus melalui persidangan sebagai mekanisme legal untuk merampas kemerdekaan seorang. Kedua, pecandu yang dikirim ke tempat rehabilitasi sebagai rangkaian dari proses hukum. Tindakan ini alih-alih untuk melakukan pemulihan, justru secara hukum dianggap bagian dari menjalani penghukuman.
Praktik serupa kerap terjadi pada panti-panti sosial bagi penyandang disabilitas mental. Mereka dikurung dalam jeruji besi sehingga tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan pihak luar. Praktik yang diklaim sebagai upaya penyembuhan justru
menghadirkan permasalahan baru karena abai terhadap pelindungan hak-hak dasar para korbannya. Praktik pengurungan seperti ini merupakan bukti akan adanya pengambilan keputusan secara sepihak, sewenang-wenang, dan di luar pengawasan medis, sehingga tergolong sebagai bentuk kejahatan.
Lebih jauh, praktik ilegal demikian berpotensi sebagai tempat penyiksaan. Temuan masyarakat sipil terhadap tempat penyiksaan biasanya dilakukan di tempat tertutup. Institusi kepolisian menempati tempat yang paling banyak terjadi penyiksaan. Terakhir kejadian yang menimpa FNS, seorang pecandu narkotika yang ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan meninggal diduga kuat disiksa karena ditemukan luka disekujur tubuhnya. Di beberapa tempat lain seperti panti-panti
rehabilitasi dan panti-panti sosial, tidak luput dari ruang potensial terjadinya penyiksaan. Situasi ini mengkhawatirkan karena praktik penyiksaan dilakukan di tempat-tempat tertutup. Dari aspek pembuktian, kondisi tersebut menghambat pengungkapan kasusnya dan menyeret pelaku. Sehingga tidak jarang, kasus-kasus penyiksaan mandek tanpa ada kejelasan status hukumnya.
Berdasarkan uraian di atas, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menuntut:
- Polri untuk meminta pertanggung jawaban hukum kepada Bupati Terbit atas tindakannya melakukan dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seorang;
- Polri menutup tempat-tempat serupa tahanan seolah-olah sebagai tempat rehabilitasi narkotika atau panti sosial;
- Penutupan oleh Polri disertai dengan koordinasi dengan lembaga negara terkait untuk memastikan hak-hak dasar para korban tidak terabaikan, khususnya perihal tempat tinggal yang layak serta menghindari stigma dari masyarakat;
- Kelompok kerja untuk pencegahan penyiksaan yang terdiri dari Komnas HAM, KPAI, Ombudsman, LPSK, Komnas Perempuan untuk mengintensifkan kembali kunjungan ke tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan.